 |
| picture by : https://trustmediaid.com/ |
Pesantren dan eksistensinya di masyarakat diakui memiliki
peran yang vital bagi kontiunitas transformasi ajaran agama maupun keilmuan
Islam di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang bahkan dalam konteks masa akan
datang. Pesantren telah menjadi katalisator bagi penyampaian visi dan misi
Islam yang didakwahkan baik pada aspek akidah, syari’ah, akhlak, sampai
pada persoalan bidang sosial, ekonomi, budaya, seni, kemanusiaan, politik
kebangsaan dan lainnya. Nilai-nilai Islam yang universal dan adiluhung itu diresepsi
oleh para ulama, direfleksikan lalu kemudian dibahasakan dalam
penjelasan-penjelasan yang disinggungkan pada konteks lokalitas masyarakat dan
umat. Maka tidak mengherankan pesan-pesan agama yang disampaikan oleh para
ulama pesantren melalui tradisi santri dan kepesantrenannya melahirkan suatu
pemahaman Islam yang dianggap “membumi” dan akrab dengan sendi-sendi
lokalitas yang menjadi bagian kesadaran masyarakat muslim di tanah air.
Demikian juga institusi Majelis ta’lim, merupakan sebuah
institusi pendidikan dan sosial keagamaan yang mempunyai akar kuat dalam
masyarakat Islam tradisional Nusantara, tidak terkecuali pada masyarakat muslim
di Kabupaten Indragiri Hilir. Bisa dikatakan majelis ta’lim dengan sistemnya
yang unik dan non-formal adalah cikal bakal pendidikan pesantren atau
madrasah selanjutnya. Berkembangnya majelis ta’lim dalam masyarakat Islam,
antara lain didorong oleh suatu tanggung jawab untuk penyebaran ilmu
dan syi’ar dakwah agama kepada masyarakat dan umat secara luas oleh
seorang ulama. Peran ulama yang memimpin majelis ta’lim mendapat
tempat tersendiri dalam bentuk penghargaan yang tinggi dari masyarakat kepada
mereka.
Kedua lembaga tradisional pendidikan Islam ini memiliki tugas
yang sama, yakni menyampaikan atau mentransformasikan pesan-pesan dan ajaran
agama kepada masyarakat dan umat dengan berbagai media. Salah satu media
penyampaian ajaran atau keilmuan dalam informasi keagamaan itu ialah melalui
tradisi pembacaan kitab-kitab karangan ulama Indonesia (Nusantara/jawi) yang
beredar sekian lama di pesantren atau majelis ta’lim, khususunya kitab
beraksara Arab- Melayu yang khas pada masyarakat berkebudayaan Melayu.
Kitab-kitab tersebut lazim dan menjadi referensi yang sering dipakai bagi
mereka, selain beredarnya juga berbagai sumber maupun literatur kitab-kitab
bahasa Arab baik yang klasik maupun kontemporer saat ini. Namun loyalitas
pada tradisi khazanah Kitab Arab-Melayu itu seakan tidak pernah surut
untuk dibaca,dipelajari serta dipahami, khususnya di Indragiri Hilir. Kemudahan
akses kebahasaan dengan aksara Arab berbahasa Melayu, turut membantu bagi
masyarakat dalam memahaminya. Karena pelajaran Arab-Melayu pada masa dahulu
sangat digalakkan dan menjadi suatu “kewajiban” mempelajarinya. Sebab bahasa
ini adalah lingua franca yang banyak digunakan di sebagian dunia Islam,
setelah bahasa Arab, Bahasa Persia/Urdu, dan bahasa Turki. Sebelum mengenal
tulisan latin yang dibawa oleh sistem pendidikan kolonial, masyarakat muslim di
Nusantara sudah terlebih dahulu mengenal akrab dan berkomunikasi dengan bahasa
lokal mereka sehari-hari, seperti Arab-Melayu ini, terutama umumya dalam dunia
persuratan.
Pengamatan atas Fenomena Tradisi Pengajian di Pesantren dan Majelis Ta’lim
Berangkat dari kenyataan tersebut-lah, terdapat hal yang
menarik untuk diteliti, kenapa para ulama pesantren dan Tuan-tuan Guru
majelis ta’lim dengan lokus pilihan pada pengajian-pengajiannya masih
terus mengajarkan kepada santri dan masyarakat akan khazanah kitab-kitab para
ulama tersebut dari dahulu hingga kini secara berkelanjutan. Sebagai sebuah
pengamatan awal di wilayah Tembilahan dan Tembilahan Hulu (barangkali menjadi
sampel representatif dari wilayah Kabupaten Inhil), sebenarnya ada banyak
variabel yang bisa dijelaskan mengenai fenomena ini. Namun, secara simpel dan
cepat bisa dikatakan tentang pengamatan terhadap terjadinya budaya itu ialah,
karena masih tingginya penghormatan (ta’zhiman) dan mengharap keberkahan
(tabarrukan) oleh para ulama terhadap pengarang kitab (muallif) yang
menjadi bacaannya itu. Pun halnya demikian pula yang dirasakan oleh
masyarakat (santri maupun masyarakat luas), ditambah faktor kemudahan resepsi
kebahasaan di banding kitab berbahasa Arab Gundul (kitab kuning). Maka, tidak
heran komunitas ini begitu “menikmati” membaca maupun menyimak seolah tanpa ada
kebosanan, setiap isi dari karya-karya beragam dari para pengarang kitab-kitab
Arab-Melayu yang mereka pelajari, semisal; Sabilal Muhtadin (fiqih) dan
Tuhfatur Raghibin (tauhid) karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari,
Siyarus Salikin dan Hidayatus Salikin (dua-duanya akhlak tasawuf) karya
Syekh Abdus Samad al-Falimbani, Furu’ul Masa’il (fiqih) dan ‘Aqidatun Najin
(tauhid) karya Syekh Daud al-Fathani, Fathul ‘Arifin (amaliah tarekat Qadiriyah
wa Naqsyabandiyah) karya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Durrun-Nafis karya Syekh
Muhammad Nafis al-Banjari, Futuhul ‘Arifin (tasawuf) karya Tuan Guru Muhammad
Sarni Alabio, Asrarus Shalah (fikih-tasawuf), Aqa’idul Iman (tauhid), Risalah
‘Amal Ma’rifah (tauhid-tasawuf), Fathul ‘Alim fi Tartibit Ta’lim (tauhid) karya
Syekh Abdurrahman Shiddiq, dan lain sebagainya yang mungkin masih ada
kitab-kitab lain, namun luput dari pengamatan ini.
Tradisi pengajaran maupun penyampaian dakwah ataupun
informasi keagamaan melalui pembacaan kitab seperti kitab-kitab Arab-Melayu ini
mesti harus terus dilanjutkan dan dilestarikan oleh pesantren dan
majelis-majelis ta’lim dengan peran maksimal dari para kyai, tuan guru, ustadz
dan santri-santri di lingkungan pesantren maupun masyarakat luas dengan
pengajian-pengajian yang diampu. Mengingat keilmuan agama perlu atas sandaran
sanad maupun referensi yang kuat, jelas dan otoritatif sebagaimana
direpresentasikan pada kitab-kitab ulama itu. Hal ini di samping bermakna upaya
mengerakkan dan melestarikan tradisi juga sebagai counter atas pola pengajian
dan dakwah saat ini yang hanya mengandalkan performance secara oral-retorik,
dan live- interaktif maupun pengajian berbasis pada mono-literal dunia maya,
namun kenyataannya “miskin” kedalaman sumber kajian. Akibatnya banyak
terjadi mis-persepsi yang bisa mereduksi pemahaman dalam informasi pengetahuan
keagamaan yang argumentatif.
Dan yang terpenting lagi dari itu semua, kitab-kitab Arab
Melayu itu adalah suatu khazanah peradaban keilmuan dan kebudayaan milik kita
yang terus harus dijaga, dirawat dan dilestarikan sampai akhir zaman. Lebih
lagi bagi institusi pesantren dan majelis ta’lim sebagai penanggung jawab
transformasi khazanah kitab-kitab Arab Melayu sekaligus jangkar tradisi Islam
di Indragiri Hilir. Khazanah ini adalah warisan literasi yang bernilai tinggi
dan mesti dilanjutkan dari generasi ke generasi tanpa henti dipelajari dan
ditekuni.
*Nasrullah,
Pengajar pada FIAI UNISI dan PP. Jilussalamah al-Islami Tembilahan.



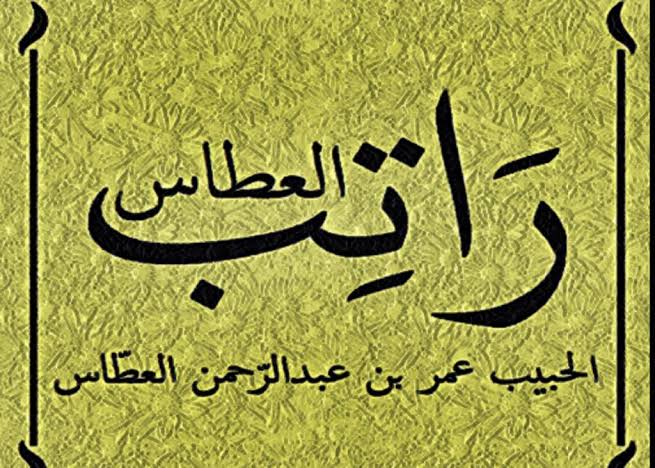

0 Komentar