M.Rofiq Aldista
A. PENDAHULUAN
Sebelum memasuki pembahasan mengenai Mantuq dan Mafhum ada baiknya kita membahas tentang Asbabun nuzul terlebih dahulu. Asbabun nuzul merupakan salah satu pokok bahasan dalam studi Ilmu-ilmu al-Qur’an, Ilmu ini memberikan peranan yang sangat penting dalam menafsirkan al-Qur’an, bukan hanya untuk memahami suatu ayat, mengetahui hikmah dibalik penetapan sesuatu hukum, tetapi juga menginformasikan realitas sosial-budaya masyarakat pada masa turunnya al-Qur’an. Kajian asbabun nuzul memberikan kesadaran akan pentingnya konteks sejarah dalam memahami al-Qur’an, dimana concern kajian ini adalah menelaah latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur’an, disamping sangat membantu untuk melacak makna dan semangat suatu ayat, juga berguna dalam upaya memahami al-Qur’an untuk waktu dan tempat yang berbeda.
Kekeliruan dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an adalah dikarenakan tidak memahami asbabun nuzul ayat tersebut. Hal ini, misalnya, pernah dialami oleh Khalifah Marwan bin Hakam dan ‘Utsman bin Mazd’un. Dalam masyarakat indonesia misalnya, ada sebagian masyarakat kita yang memahami ungkapan yang sangat populer “fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan” berdasarkan ayat al-Fitnatu Asyaddu min al-Qatl, atau al-Fitnatu Akbaru min al-Qatl yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 191 dan 217. Kesalahan itu terjadi, karena di samping memahami arti kata “al-fitnah” dalam ayat itu semakna dengan arti fitnah dalam bahasa indonesia, juga disebabkan mengabaikan asbabun nuzul yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.
Oleh karena itu, sangat tepat apa yang pernah di kemukakan oleh al-Wahidi an-Naisaburi bahwa “tidak mungkin bisa memahami suatu ayat tertentu tanpa mengetahui latar belakang sejarah turunnya ayat tersebut” . Lebih jauh, ia menyatakan bahwa “asbabun nuzul adalah bidang ilmu al-Qur’an yang paling penting untuk dicermati dan diperhatikan, sebab penafsiran dan pengungkapan maksud dari suatu ayat tidak akan dapat dilakukan tanpa mengetahui kronologis yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut.
Ketika kita berbicara mengenai ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur’an, sebenarnya dari semua ayat yang ada didalam Al-Qur’an tersebut tidak semuanya memberikan arti/pemahaman yang jelas bagi kita. Jika kita mau telusuri, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang masih butuh penjelasan yang lebih mendalam mengenai hukum yang tersimpan dalam ayat tersebut.
Sebagaimana Al- Qur’an yang berdampingan dengan hadist nabi Muhammad, merupakan petunjuk yang dipercaya oleh umat Islam sebagai pedoman hidup. Keduanya juga merupakan sumber utama penerapan hukum hukum syari’ah. Dari apa yang diredaksikan didalam Al-Qur’an dan hadist, ada yang dapat dipahami dengan apa adanya, tidak lebih dan tidak kurang. Namun adakalanya harus masuk ke kedalaman kata atau kalimat yang terkandung di dalamnya sehingga lahir makna-makna baru yang tidak berhubungan langsung dengan apa yang tertuliskan, kendati dari jauh ada hubungannya. Petunjuk (dalalah) lafaz kepada makna adakalanya berdasarkan pada bunyi (Mantuq, arti tersurat) perkataan yang diucapkan itu, baik secara tegas maupun mengandung kemungkinan makna lain, dengan taqdir maupun tanpa taqdir. Dan adakala-Nya pula berdasarkan pada pemahaman (Mafhum, arti tersirat)-Nya, baik hukumnya sesuai dengan hukum Mantuq ataupun bertentangan. Inilah yang dinamakan dengan Mantuq dan Mafhum. Maka, dalam menetapkan suatu hukum, diperlukan adanya usaha untuk melakukan pengamatan dan penelitian guna mengetahui apa yang tersirat dari teks Al-Qur’an dalam hadist tersebut. Dari sinilah para ulama menciptakan Mantuq dan Mafhum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi mantuq dan mafhum, macam macam mantuq dan mafhum dan mengambil hijjah dari mantuq dan mafhum.
B. DEFINISI MANTUQ DAN MACAM MACAMNYA
Mantuq adalah sesuatu (makna) yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukkan makna berdasakan materi huruf huruf yang diucapkan. Mantuq itu ada yang berupa nass zahir dan mu’awwal. Nass ialah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara Tegas (sarih), tidak mengandung kemungkinan makna lain.
Mu’awwal adalah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh karena ada sesuatu dalil yang menghalanginya dimaksudkannya makna yang rajah. Mu’awwal berbeda dengan zahir, zahir diartikan dengan makna marjuh karena ada dalil yang memalingkannya dari makna rajih. Akan tetapi masing masing kedua makna itu ditunjukkan oleh lafaz menurut bunyi ucapnya.
Apa itu Marjuh?
Marjuh adalah (makna yang dikuatkan) dalam kekuasaannya. Ketika menggunakan ayat ini, umumnya mufassir menggunakan takwil. Yakni mengalihkan makna rajih (tangan) kepada marjuh (kekuasaan) karena ada alasan (dalil) yaitu ketidak mungkinan allah memiliki tangan dalam arti indrawi.
• Dalalah iqtida dan Dalalah Isyarah
Kebenaran petunjuk (dalalah) sebuah lafaz kepada makna terkadang bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Dalalah demikian disebut dalalah iqtida. Dan terkadang tidak bergantung pada hal tersebut tetapi lafaz itu menunjukkan makna yang tidak dimaksud pada mulanya. Yang demikian disebut adalah isyarah. Termasuk Ijazul-Qasr (pemadatan kalimat untuk meringkas). Dinamakan Iqtida karena perkataan tersebut menuntut sesuatu tambahan lafaz (lain) atas lafaz yang ada.
Kedua dalalah ini, iqtida dan isyarah, juga berdasarkan pada mantuq, maka keduanya termasuk bagian dari mantuq. Dengan demikian, mantuq meliputi:
a) nass,
b) zahir,
c) mu’awwal,
d) iqtida, dan
e) isyarah.
C. DEFINISI MAFHUM DAN MACAM-MACAMNYA
Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan. Ia terbagi menjadi dua, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah.
Mafhum muwafaqah ialah makna yang hukumnnya sesuai dengan mantuq. Mafhum ini ada dua macam :
• Fahwal khitab, yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih harus diambil hukumnya dari pada mantuq. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua.
Contohnya firman Allah swt dalam QS. Al-Isra’ ayat 23:
فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
“Janganlah kamu mengatakan kata-kata keji kepada dua orang ibu bapakmu.”
Sedangkan kata-kata keji saja tidak boleh (dilarang) apalagi memukulnya.
• Lahnul khitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hokum mantuq..
Seperti firman Allah swt.:
إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ اٌلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ نَارًاصلى وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim secara aniaya sebenarnya memakan api kedalam perut mereka” .
Kedua mafhum ini disebut mafhum Muwafaqah karena makna yang tidak disebutkan itu hukumnya sesuai sesuai dengan hukum yang diucapkan, meskipun hukum itu memiliki nilai tambah pada yang pertama dan sama pada yang kedua. Dalalah dalam mafhum muwafaqah itu termasuk dalam kategori “ mengingatkan kepada yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi”. Kedua macam ini terkumpul dalam firman allah.
• Mafhum mukhalafah, ialah makna yang berbeda hukumnya dengan Mantuq. Mafhum ini ada empat macam:
Seperti dalam firman Allah swt pada QS. al-Jum’ah ayat 9:
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
“Apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkan jual beli.”
Mafhum mukhalafah sendiri terbagi menjadi :
• Mafhum al-Washfi (pemahaman dengan sifat) adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat, menghubungkan hukum sesuatu kepada syah satu sifatnya.
Dalam mafhum sifat terdapat tiga bagian, yaitu mushtaq, hal (keterangan keadaan) dan ‘adad (bilangan). Misalnya pada sabda Rasulullah saw.:
فِي السَّائِمَةِ زَكاَةِ
“para binatang yang digembalakan itu ada kewajiban zakat”
Mafhum mukhalafahnya adalah binatang yang diberi makan, bukan yang digembalakan.
Mafhum Sifat ada 3 macam:
• Mustaq dalam ayat.
Contohnya dalam QS. Al-Hujarat ayat 6:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”
Dapat dipahami dari ungkapan kata ‘fasiq’ ialah orang yang tidak wajib ditelliti beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seseorang yang adil wajib diterima.
• Hal (keterangan keadaan)
Seperti fiman Allah, QS. Al-Maidah ayat 95:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makanan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”
Ayat ini menunjukkan tiadanya hukum bagi orang yang membunuhnya karena tak sengaja. Sebab penentuan “sengaja” dengan kewajiban membayar denda dalam pembunuhan binatang buruan tidak sengaja.
• Adad (bilangan)
Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 197:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ
“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasikh dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal.”
Mafhumnya ialah melakukan ihram diluar bulan-bulan itu tidak syah.
1. Mafhum illat adalah menghubungkan hukum sesuatu karena illatnya. Mengharamkan minuman keras karena memabukkan
2. Mafhum ghayah (pemahaman dengan batas akhir) adalah lafal yang menunjukkan hukum sampai pada ghayah (batasan, hinggaan), hingga lafal ghayah ini ada kalanya dengan “illa” dan dengan “hatta’. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6:
اِذَا قُنْتُمْ اِلىَ الصَّلَوةِ فاَغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ واَيْدِيَكُمْ أِلىَ الْمَرَافِقِ....
“bila kamu hendak nmengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kepada siku”.
Mafhum mukhalafahnya adalah membasuh tangan sampai kepada siku.
3. Mahfum laqaab (pemahaman dengan julukan) adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau isim fiil. Seperti firman Allah SWT:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.” Mafhum mukhalafahnya adalah selain para ibu.
4. Mafhum hasr adalah pembatasan. Seperti dalam firman Allah swt.:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.”
Mafhum mukhalafahnya adalah bahwa selain Allah tidak disembah dan tidak dimintai pertolongan. Oleh karrena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya Dia-lah yang
5. Mafhum syarat , adalah petunjuk lafadz yang memberi fadah adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Seperti dalam surat al-Thalaq ayat 6:
...وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ...
“...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mererka nafkahnya.”
Mafhum mukhalafahnya adalah istri-istri tertalak itu tidak sedang hamil, tidak wajib diberi nafkah.
D. BERHUJJAH DENGAN MAFHUM
Berhujjah dengan mafhum masih diperselisihkan. Menurut pendapat paling sahih, mafhum mafhum tersebut boleh dijadikan hujjah (dalil,argumentasi) dengan beberapa syarat lain :
• Apa yang disebutkan bukan dalam rangka “kebiasaan” yang umum. Maka kata-kata “yang ada dalam peliharaanmu”
• Apa yang disebutkan itu tidak untuk menjelaskan suatu realita.
Mantuq sudah jelas bisa dijadikan hujjah, karena lafalnya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaqah. Para ulama’ bersepakat, bahwa semua mafhum bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali mafhum laqaab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim ‘alam atau isim jenis itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum padanya bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya, kecuali jika ada dalil lain yang menentukannya. Seperti firman Allah : “Muhammad adalah utusan Allah.”
Ayat tersebut jika diambil mafhum mukhalafahnya akan memberikan pengertian bahwa selain Nabi Muhammad addalah utusan Allah. Inii jelas bertentangan dengan nash yang ada.
Berhujjah dengan mafhum masih diperselisihkan. Menurut pendapat yang paling shahih, mafhum-mafhum tersebut boleh dijadikan hujjah (dalil, argumentasi) dengan beberapa syarat, antara lain:
Apa yang disebutkan bukan dalam kerangka “kebiasaan” yang umum. Misalnya “yang ada dalam pemeliharaanmu” dalam QS. An-Nisa’ :23 yang artinya “... dan anak-anak perempuan dan istri-istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu...”, ini tidak ada mafhumnya (maksudnya ayat ini tidak dapat dipahami bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya boleh dinikahi), sebab pada umumnya anak-anak perempouan istri kitu berada dalam pemeliharaan suami. Apa yang disebutkan itu tidak untuk menjelaskan suatu realita. Seperti firman Allah QS. Al-Mu’minin: 117 ; yang artinya “ Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.”
Dalam kenyataannya Tuhan manapun selain dari Allah tidak ada dalilnya. Jadi kata-kata “ padahal tidak ada satu dalilpun baginya tentang itu” adalah suatu sifat yang pasti yang didatangkan untuk memperkuat realita realita dan untuk menghinkan orang yang menyembah Tuhan di samping Allah, bukan untuk pengertian bahwa menyembah Tuhan-tuhan itu boleh asal dapat ditegakkan dalilnya.
F. PENUTUP
Dari pembahasan diatas, bahwa definisi mantuq adalah sesuatu (makna) yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukkan makna berdasakan materi huruf huruf yang diucapkan. Mu’awwal adalah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh karena ada sesuatu dalil yang menghalanginya dimaksudkannya makna yang rajah. Mu’awwal berbeda dengan zahir, zahir diartikan dengan makna marjuh karena ada dalil yang memalingkannya dari makna rajih. Akan tetapi masing masing kedua makna itu ditunjukkan oleh lafaz menurut bunyi ucapnya. Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan. Ia terbagi menjadi dua, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah.
Mafhum muwafaqah ialah makna yang hukumnnya sesuai dengan mantuq. Mafhum ini ada dua macam :
• Fahwal khitab, yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih harus diambil hukumnya dari pada mantuq. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua.
• Lahnul khitab, yaitu apabila hokum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuq
DAFTAR PUSAKA
Al-Qattan, Manna Khalil. 1992. Studi ilmu-ilmu Qur’an. Mudzakir AS. 1996.PT. Pustaka Litera AntarNusa. Bogor
Brainly Com
Makalah Agama Islam http://makalahpendidikanislamlengkap.blogspot.com/2013/06
Syafril 2018. Asbabun Nuzul : Kajian Historis Turunnya Ayat al-Qur’an. Vol VI, No 2



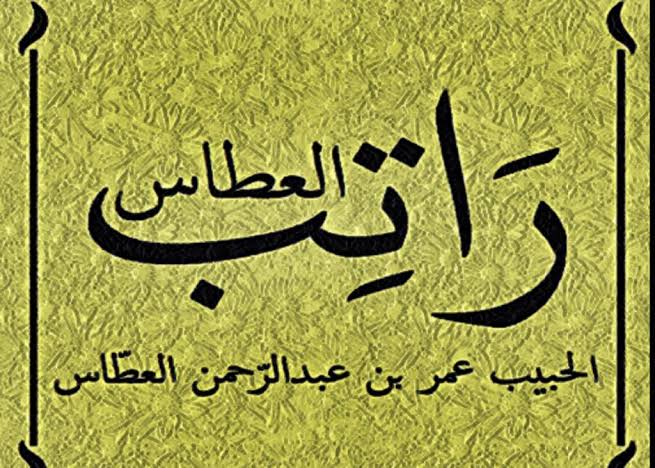

0 Komentar