PENDAHULUAN
Dalam upaya memperdalam suatu ilmu pengetahuan, setiap orang dituntut untuk mengetahui dasar-dasar umum ilmu pengetahuan tersebut. Selain itu dituntut pula untuk memiliki pengetahuan yang cukup dan mendalam mengenai beberapa ilmu lain yang berkaitan dengannya. Hal ini dimaksudkan agar upaya memahami ilmu pengetahuan itu tidak salah dan asal-asalan. Sehingga ketika melakukan pengkajian terhadap suatu ilmu, ia tidak mengalami suatu kesulitan yang dapat menyebabkan tidak tepatnya sasaran penelitian.
Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan beberapa hal yang dapat membantu mudahnya mengkaji ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tafsir. Diantaranya yakni kaidah-kaidah penafsiran yang tepat. Untuk itu, dalam mempelajari tafsir diperlukan kaidah-kaidah penafsiran agar bias mengetahui dan memahami penafsiran dengan tepat.
PEMBAHASAN
Pengertian kaidah tafsir
Qawa`id Al-Tafsir Qawa`id adalah bentuk jamak dari Qa`idah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kaidah” dengan makna: rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil (dalam matematika).4 Dalam bahasa Arab makna Qaidah adalah: peraturan, prinsip, dasar, asas, pondasi, model, pola, mode.
Khalid bin Usman al-Sabt, seorang ulama kontemporer mendefinisikan kaidah sebagai: ﺣﻛم ﻛﻠﻲ ﯾﺗﻌر ف ﺑﮫ ﻋﻠﻲ أﺣﻛﺎم ﺟزﺋﯾﺎﺗﮫ Tafsir secara etimologi bermakna; menyingkap/membuka dan penjelasan mengeluarkan sesuatu dari tempat tersebunyi/samar ke tempat yang jelas/terang. Definisi tersebut menegaskan bahwa kaidah mencakup semua bagian-bagiannya. Maka kaidah tafsir didefinisikan sebagai “Ketentuan umum yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan al-Qur’an”. Namun dalam kenyataan sering ditemukan bagian yang menyimpang dari kaidah umum itu. Ada ulama yang menyatakan ketika melihat kenyataan tersebut bahwa memang demikian sifat kaidah, terutama dalam hal-hal yang bersifat teoritis. Maksudnya, walaupun rumusan definisi “kaidah” mengandung makna bahwa ia mencakup segala rinciannya, namun secara substansial sejak awal para perumus tidak memaksudkan dari kata kully/ umum mencakup segala sesuatu tanpa kecuali. Para pakar bahasa sering menyebut bahwa apa yang tidak tercakup dalam kaidah disebut Syadz. Tapi dalam kaidah tafsir hal tersebut tidak berlaku, karena objeknya adalah Alqur’an. Tidak mungkin kita menyatakan suatu ayat/surah dalam Alqur’an salah hanya karena tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Apalagi kaidah disusun oleh para perumus (ulama) jauh setelah Alquran diturunkan. Kalau ada ayat yang kelihatannya menyimpang dari kaidah, itu karena kelemahan perumus dalam merumuskan, atau karena kasusnya sangat jarang terjadi, atau karena ada pertimbangan-pertimbangan makna yang mendorong dipilihnya sesuatu yang dinilai menyimpang tersebut. ( Syamsuri, Skripsi: Pengantar Qawa`Id Al-Tafsir, Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, tt)
Kaidah Penafsiran Linguistik
Linguistik adalah satu cabang yang meneliti perkembangan Bahasa manusia mulai dari bibit atau embrio bahasa sampai muncul menjadi bahasa yang di gunakan untuk mengungkapka pemikiran mereka. Linguistiq meneliti fase-fase perkembangan yang dilalui oleh suatu bahasa sampai pada fase bunyi yang mengandung makna ungkapan dan kaedah dasar yang di gunakan manusia dalam penggunaan bahasa mereka. Linguistik juga meneliti sampel kata yang di gunakan manusia untuk menentukan makna semantik dan penggunaan semiotika bahasa.
Sebagaimana linguistiq menelusuri bahasa sampai pada fase bunyi yang mengandung makna ungkapan dan kaedah dasar yang di gunakan manusia sampai menjadi bahasa bangsa. Linguistik juga meneliti sampel kata yang di gunakan manusia untuk menentukan makna semantic dan penggunaan semiotika bahasa, sebagaimana linguistiq juga meneliti pusat-pusat bahasa dimana pusat bahasa tesebut di bangun sebagai symbol peradaban manusia dan lain-lainnya yang merupakan cerminan barometer kebudayaan manusia dari bahasa yang di gunakan, semua hal tersebut di kenal dalam ilmu linguistiq perkembangan atau aslu al lughah atau origine du laugage.
Menurut Ali al-Usiy, linguitsik merupakan salah satu metode dalam penafsiran al-qur’an. Metodologi linguistik merupakan suatu alat untuk menguraikan dan menjelaskan apa-apa yang dikandung dalam al qur’an. Oleh karena itu, metodologi adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pokok dalam penelitian. Para penganut metodologi ini cenderung mempergunakan Bahasa dalam menjelaskan problem mengartikan ayat-ayat al-qur’an. Mereka saling memandang al-quran sebagai suatu teks agama, juga memandang sebagai teks sastra yang kemukjizatan. Al-Sayyid Khalil beranggapan bahwa metode lingustik dalam penafsiran al-qur’an ini memiliki keistimewaan sendiri. Susun kata-kata yang dipakainya berbedha dengan metodologi yang lain. Ia mampu menguraikan sebuah susunan kalimat dalam suatu ayat dengan memakai kalimat-kalimat dan huruf-huruf yang ada di dalam ayat trsebut tanpa memakai kalimat dan huruf yang lain. (Azman Arsyad, Jurnal: Teknik Interpretasi Linguistic Dalam Penafsiran A- Qur’an, (Makasar: UIN Alauddin,tt), hlm. 167
Metode Penafsiran Linguistik (Lughowi)
Tujuan alqur`an diturunkan Allah SWT. salah satunya adalah berfungsi sebagai huda li an-nas (petuunjuk bagi manusia). Di dalamnya terkandung sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Di sisi lain, terkandung ayat-ayat muhkam dan mutasyaabih, `am (umum) dan khas (khusus), mutlaq dan muqayyad, mubham (ambigu) dan mubayyan. Dilihat dari aspek lain, al-qur`an tersusun dengan memakai gaya bahasa yang mengandung haqiqah dan majaz, tashrih dan kinayah.
Bertitik tolak dari situ, peranan tafsir sangat urgen ketika hendak menjadikan al-qur`an sebagai petunjuk bagi manusia. Secara diakronis, corak penafsiran yang ditempuh oleh para mufassir (interpretator) ada dua macam :
Tafsir bil-riwayah (tafsir bil-ma`tsur), menurut para ulama corak tafsir ini adalah yang pertama kali muncul. Pada dasarnya jenis tafsir ini menjadikan ayat suci al-qur`an, hadis Nabi, dan apa-apa yang datang dari para shahabat dan tabi`in sebagai alat untuk menafsirkan al-qur`an.
Tafsir bil-ra`yi, salah satunya muncul sebagai akibat berinteraksinya umat islam dengan peradaban Yunani yang banyak menggunakan akal. Oleh sebab itulah dalam tafsir bil-ra`yi peranan akal sangatlah dominan, namun tentu tetap mencantumkan dalil naqliyahnya. Pada perkembangan selanjutnya, tafsir bil-ra`yi melahirkan beberapa metodologi tafsir yang berbeda-beda seiring dengan kecenderungan mufassir. ( Drs. Rosihon Anwar, M.Ag,2001: 256-257).
Format Penafsiran Lughawi dan Tokohnya
Dengan menggunakan metode-metode penafsiran ini, mufassir berpendapat bahwa al-qur`an tersusun dengan menggunakan bahasa arab yang mengandung nilai balaghoh yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sangat perlu untuk menafsirkan al-qur`an dari segi bahasanya. Tentunya dari segi aspek-aspeknya, termasuk di dalamnya ilmu nahwu (gramatikal), al-isyitiqaq (derivasi), tashrif, dll.
Mufassir yang pertama kali menjadikan bahasa sebagai titik tolak dalam penafsiran al-qur`an adalah Al-Farra (wafat 207 H). Kemudian disusul oleh Abi Ubaidillah (wafat 210 H). Tsaib (wafat 219 H). Adapun Ath-Thabari (wafat 310 H) yang memadukan antara riwayat dan bahasa. Demikian pula az-Zamakhsari (wafat 538 H) dalam kitabnya Al-Muharrarul Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-`Aziz.
Sebagian mufassir yang menempuh pendekatan ini menggunakan syair-syair pra-islam (jahiliyah) sebagai salah satu referensi dalam menetapkan arti kata-kata dalam al-qur`an. Langkah ini ditempuh, umpamanya, oleh Ath-Thabari dan Ibn Abbas. Ibnu Abbas berkata : Jika kalian menanyaiku tentang makna gharib dalam al-qur`an, aku akan menjawab lihatlah syair-syair arab.” Dan ketika menafsirkan ayat :
فانزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء
Ibnu Abbas berkata, “setiap apa yang berada dalam kitab Allah mengandung rijs jika ditentang, yakni siksaan.”
Contoh lain mengenai kitab menempuh metode linguistik adalah kitab Al-Kasyaf `an Haqa`iqut Tanzil Wa Uyun al-Aqwil Fi Wujuh at-Ta`wil yang ditulis oleh az-Zamakhsari. Ia memiliki keistimewaan yang membedakannya dari mufassir sebelumnya. Keistimewaan tersebut berhubungan dengan paparannya tentang rahasia-rahasia balaghah yang terkandung dalam al-qur`an. ( Drs. Rosihon Anwar, M.Ag,2001:257).
Kaidah penafsiran idzhar, idhmar, ziyadah, dhohir, taqdim, ta’khir.
Kaidah Idzhar dan Idzmar
Kajian tentang dhomir ini sangat penting karena mengenai pemahaman ayat banyak yang bergantung pada penguasaan dhomir tersebut. Hal ini telah lama menjadi perhatian dari ulama tafsir yang mana dari uraian ini, informasi yang diberikan yang biasa di kaji yaitu berdasarkan tiga buku yakni al-burhan, karangan al- Zarkasyi, al-itqan, karangan al-Suyuthi, dan mabahis, karangan Manna al-Qathan.
Dalam hal ini al-Qur’an ketika menyampaikan informasi jug sering menggunakan dhomir sebagaimana di terapkan dalam bahasa Arab tersebut. Kata ganti dalam bahasa mempunyai peranan yang sangat penting, seperti untuk meringkas suatu pembicaraan tanpa mengurangi makna yang dikandungnya, karena dhomir dapat berfungsi menggantikan kedudukan sejumlah kata tanpa merusak makna yang dikandungnya sedikitpun. Seperti pada lafadz “hum” yaitu dalam firman allah yaitu di ujung ayat 35 al-Ahzab, misalny, menempati tempat duap uluh kata yang di sebutkan sebelumnya. ( Azman Arsyad, Jurnal: Makasar: UIN Alauddin,tt), hlm. 167).
Idzhar secara bahasa berarti sesuatu yang menerima pada kesamaran dan penyamaran. Bahwasannya idzhar itu berarti jelas sehingga disamarkan ataupun disimpan. Ibnu Faris berkata, kata idzhar berasal dari kata dho’ ha’ ro’ yang merupakan huruf sohih yang menjadi satu dan menunjukkan pada kekuatan dan kejelasan, dari ketentuan diatas contohnya : ظهر الشيئ, يظهر, ظهورا فهو ظاهر
Idzhar secara istilah ialah menjelaskan dengan lafadz dan dan menjelaskan di dalam tempat yang bisa digantikan dengan yang tersimpan.
Pengertian idhmar secara bahasa ialah Ibnu Faris berkata “ dho’ mim dan ro’ keduanya aslinya adalah huruf sohih, salah satunya menunjukkan pada kelembutan kata dan yang lainnya menunjukkan pada kesamaran dan tertutup. Maksud yang kedua ini ialah benda yang tersimpan yang tidak bisa diharapkan, dan setiap sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan Idhmar secara istilah ialah menggugugurkan sesuatu pada lafadznya bukan maknanya.
Qoidah:
Meletakkan isim dzohir ditempat isim dhomir dan sebaliknya unuk sesuatu yang bagus atau istimewa
Asal dari isim itu jelas, dan asalnya orang berbicara pun demikian sebagaimana asal di dalamnya ketika disebut dengan yang kedua itu menyebutkannya dengan dhomir karena tercukupinya dengan isim dzohir yang disebutkan di awal. Maka ketika adany perbedaan dalam asal ini mengharuskan pada tujuan yang bagus yang diinginkan dari orang yang berbicara dan itu diketahui dari susunan kata dan qarinah yang menunjukannya. Contoh :
Menempatkan isim dhomir di tempat isim dzohir
Allah ta’ala berfirman: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيئ عليم asalnya bisa dikatakan “وهو بكل شيئ عليم dan yang demikian itu dikeluarkan dari asalnya karena bertujuan untuk a’dzim (memulyakan).
Allah ta’ala berfirman "اولئك حزب الشطان الا ان حزب الشيطان..." bisa dikatakan "الا انهم" dan yang demikian itu dikeluar dari asalnya karena bertujuan untuk merendahkan dan meremehkan.
Allah ta’ala berfirman: "من كان يريد العزة فللله العزة جميعا" bisa dikatakan: "فلله هي جميعا" dan yang demkian itu dikeluarkan dari asalnya karena untuk meremehkan dengan menyebutkan isim dzohir.
Allah ta’ala berfirman: "يلوون السنتهم با لكتاب, لتحسبه من الكتاب,وما هو من الكتاب" pengulangan mengingat kitab merupakan penambahan ketetapan.
Perumpamaan penempaan isim dhomir di tempat isim dzohir
Allah ta’ala berfirman:
من كان عدوا الجبريل فانه نزل علي قلبه
Pemgucapan di dalam illat dhomir pada kalimat فانه menunjukkan tafkhim
Allah ta’ala berfirman:
انا انزلناه في ليلة القدر
Ucapan di dalam kalimat ini merupakan ucapan yang sama seperti pada contoh yang sebelumnya.
Mengulangi isim dzohir dengan maknanya yang lebih bagus dari pada mengulangi dengan lafadznya, dan mengulangi dengan isim dzohir setelah panjang lebih baik dari pada isim dhomir.
Tidak jelas bahwa mengulangi lafadz pada tempat yang dekat itu penting bagi pendengar. Hal ini jika dalam dua lafadz di dalam satu kalimat. Adapun jika salah satu dari dua lafadz di dalam jumlah yang berbeda, maka ini lebih mudah karena terpisahnya bagian dari dua kalimat.
mengulangi dengan isim dzohir setelah panjang lebih baik dari pada isim dhomir macamnya ada dua yaitu:
pertama, menjauhkan dua lafadz dapat ,enghilangkan kesulitan. Kedua, megulangi isim dzohir setelah panjang dapat mencegah fokus dalam....dalam mengembalikan marji’nya dhomir. Dan jelas bahwa ini dapat menghilangkan makna yang dikehendakinya.
Keterangan:
Contoh pengulangan isim dzohir dengan maknanya di dalam tempat yang lebih bagus
والذيين يمسكون بالكتاب واقام الصلاة انا لانضيع اجرالمصلحين.
Tidak diucapkan انا لانضيع اجر الذين يمسكون بالكتاب
Pengulangan dengan lafadz yang lain itu menunjukkan perkara sabaq.
Contoh pengulangan lafadz pada salah satu dua lafadz yang jatuh pad a kalimat yang penting dari lainnya.
واذاجاءتهم اية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتي رسل الله, الله اعلم حيث يجعل رسالته
Dalam ayat ini terdapa pengulangan lafadz jalalah
Contoh pengulangan lafadz dzohir setelah panjang
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه
Setelah itu ayatnya berbunyi:
واذقال ابراهيم لابيه ازر...
Kebiasaan orang orang arab yang selalu menyimpan pada setiap ulasan.
Contoh:
سورة انزناها وفرضناها
Lafadz سورة maksudnya ialah هذه سورة
Setiap perbuatan yang disandarkan pada Allah yang disebutkan dalam al qur’an maka diperbolehkan menyimpan lafadz Allah walaupun tidak disebutkan lebih dulu.
Contoh:
انزل من السماء ماء
Maksudnya bisa الله انزل atau انزل الله.... ( Khalid bin Usman as-sabt, tk: Dar Ibn Affan, tt), hlm 338-345).
Kaidah Ziyadah dan Nuqsan
Secara terminologi para ulama’ berbeda pendapat mengenai definisi ziyadah. Perbedaan itu disebabkan tujuan penggunaan ziyadah. Ulama nahwu dan ulama` tashrif mengatakan bahwa ziyadah ialah lafadz yang tidak mempunyai posisi di dalam i’rab, artinya ziyadah bagi mereka bukan terletak pada makna namun terletak pada lafadz-lafadz tersebut. Ulama` lughoh berpendapat bahwa ziyadah merupakan penambahan huruf atau lafadz yang tidak mempunyai arti dan faedah sama sekali. Ulama tafsir sama dengan ulama’ nahwu, terlebih bahwa ziyadah tidak mungkin terjadi dalam al qur’an jika yang dimaksud ziyadah adalah penambahan huruf atau lafadz yang tidak berfaedah, namun ulama’ tafsir mengingatkan agar berhati-hati dalam menggunakan istilah ziyadah karena itu dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat awam.
Di antara dua redaksi yang hampir sama tersebut, bahwa ada yang mempunyai kata atau kalimat yang tidak sama jumlahnya, sehingga bila diperbandingkan kedua redaksi tersebut akan terlihat pemakaian kata yang berlebihan dan kurang, karena ada kata atau kalimat yang di pakai dalam suatu redaksi terhadap redaksi lain yang mirip dengannya, tidak memakai kata atau kalimat itu. Dengan demikian terjadilah apa yang disebut ziyadah dan nuqsan (berlebih dan berkurang) dalam pemakaian kata.
Kemiripan redaksi serupa itu banyak dijumpai dalam al qur’an, yakni urutan kedua setelah kelompok yang pertama dengan jumlah kasus sebanyak 130 buah. Contoh redaksi yang kelompok pertama ialah , ذلك الفوز العظيم, ذلك هو الفوز العظيم dan وذلك الفوز االعظيم jelas terlihat berlebih dan berkurang kata yang dipakai dalam ketiga redaksi itu. Yang pertama tidak memakai. هوdan و sementara redaksi yag kedua memakai هو dan redaksi yang ketiga memakai و , contoh lain misalnya ارايتكم dan ارايتم di dalam surat al an’am ayat 47:
قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله
Dan ayat 46:
قل ارايتم ان اخذالله
Di dalam dua ayat itu tampak dengan jelas terjadi berlebih dan berkurang dalam pemakaian kata karena redaksi yang pertama menggunakan lafadz ارايتكم dengan memakai kata fanti orang kedua كم sedangkan yang kedua hanya memakai ارايتم tanpa. كم juga termasuk dalam kategori redaksi الا تسجد dalam ayat 12 dari Al A’raf ما منعك الا تسجد اذ امرتك dan redaksi ان تسجدdi dalam ayat 75 dari surat shad:
ما منعك ان تسجد لما خلقت
Tampak dengan jelas, redaksi berlebih lafadznya dari redaksi yang kedua karena yang pertama memakai huruf لاyang terletak antara انdan تسجد , sebaliknya redaksi yang kdua tidak memakai huruf itu.
Term “berlebih dan berkurang” dalam konteks ini tidak berkonotasi positif dan negatif, melainkan sekedar untuk menggambarkan bahwa antara dua redaksi yang bermiripan itu mempunyai sedikit perbedaan redaksional sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan di dalam masing-masing redaksi itu. Maka sekalipun sebuah redaksi memakai kosa kata yang jumlahnya kurang dari redaksi yang lain, namun konotasinya tetap positif. Jadu tudak ada ayat-ayat al quir’an yang bersifat negatif baik dari susuannan redaksinya maupun pemilihan kata dan kandungan maknanya, semua bernilai positif sesuai pesan (petunjuk) yang dibawanya. ( Nasruddin Baidan,2011: 81-83).
kaidah Qadhim wa Ta’khir
Takhir yaitu kata yang trletak ada pada sesudah kata atau terkemudian (mengemudiankan) misalnya : pada kalimat “fissamaawati walaa fiilardhi” kemudian pada surat saba’ ayat 3 dan 22“ fiilardhi walaa fissamaa’I” kemudian di dalam surat yunus 61 dan Ali Imran tampak dengan jelas di dalam dua redaksi itu terjadi terdahulu dan terkemudian, karena didalam redaksi prtama lafal “al-ardu” terletak terkemudian dari as-samai,sebaliknya di dalam redaksi kedua lafal trsebut di tempatkan terdahulu darinya. Dari kedua bagian tersebut inilah yang disebut dengan taqdim wa takhir. ( Nasrudin Baidan,2002:86).
Keistimewaan dan Kelemahan Tafsir Lughawi
Keistimewaan Tafsir Lughawi
Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami al-qur`an
Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya
Mengikat mufassir dalam teks ayat-ayat, sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas berlebihan.
Kelemahan Tafsir Lughawi
Terjerumusnya mufassir dalam uraian kebahasaan yang bertele-tele sehingga uraian tentang pesan pokok al-qur`an menjadi kabur
Seringkali konteks turunnya ayat (asbab an-nuzul) atau sisi kronologisnya ayat-ayat tersebut bagaikan turun bukan dalam satu masa atau berada di tengah-tengah masyarakat tanpa budaya. Wallahu `alam. ( Drs. Rosihon Anwar, M.Ag.2001:258).
KESIMPULAN
Kaidah penafsiran linguistik merupakan aturan yang bersifat umum, kaidah secara bahasa adalah peraturan, prinsip, dasar, asas, atau pondasi. Sedangkan kaidah kebahasaan didefinisaikan sebgai ketentuan umum yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan al-qur’an. Linguistik adalah satu cabang yang meneliti perkembangan Bahasa manusia mulai dari bibit atau embrio bahasa sampai muncul menjadi bahasa yang di gunakan untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Contoh kitab menempuh metode linguistik adalah kitab Al-Kasyaf `an Haqa`iqut Tanzil Wa Uyun al-Aqwil Fi Wujuh at-Ta`wil yang ditulis oleh az-Zamakhsari. Dalam kaidah bahasa sendiri terdapat macam macam kaidah seperti kaidah idhmar dan idzhar, ziyadah nuqson, dan taqdim wa ta’khir.
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Rosihon. 2001. Samudera Al-Qur`an. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Arsyad, Azman. tt. Jurnal: Teknik Interpretasi Linguistic Dalam Penafsiran Al- Qur’an. Makasar: UIN Alauddin.
Al Usmain, Ibnu Sholih. tt. Ushul At Tafsir. tk: tp.
Baidan, Nasruddin. 2011. Metode Penafsiran Al Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ibnu Usman As Sabt, Khalid. tt. Qawaid at-Tafsir Jam`an Wa Dirasatan Juz I. tk: Dar Ibn Affan.
Syamsuri, syamsuri. tt. Skripsi: Pengantar Qawa`Id Al-Tafsir, Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.



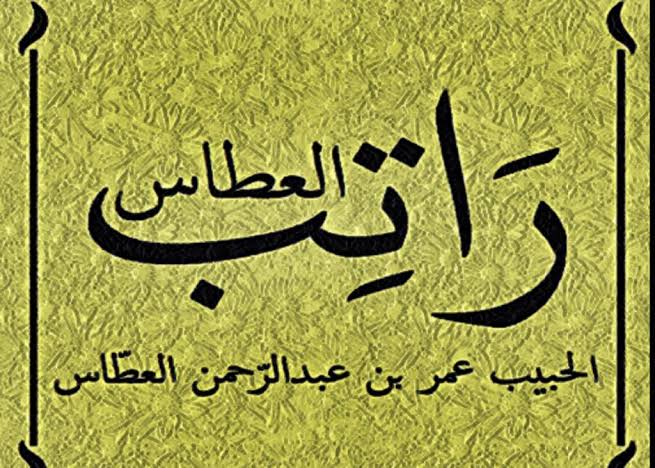

0 Komentar